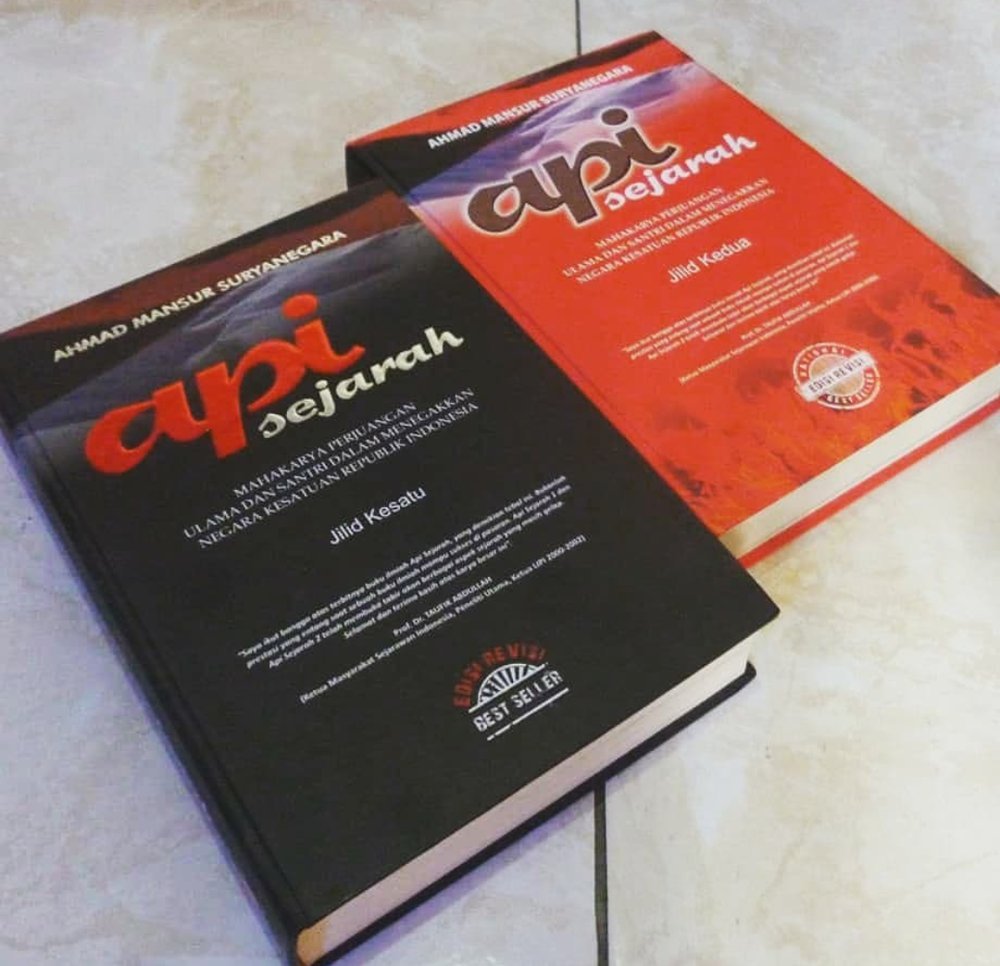Jon Afrizal*
Bulan pertama menjadi wartawan di awal tahun 2002, seorang guru berkata kepadaku, “Pergilah ke Pasar Angsoduo. Pelajari manusia yang banyak di sana.”
Aku mengingat kata-kata itu, “pelajari manusia di sana”, sembari memasuki pasar yang, ehm, penuh dengan genangan air berlumpur itu. Ada sesuatu perasaan jengah, yang tidak seperti pekerjaan bagiku.
Aku berusaha nenempatkan diri dengan baik, di antara celana jeans dan kemeja tersetrika rapi yang ku kenakan, dan riuhnya suara manusia bersautan.
Hari itu, tugasku hanya berkeliling dari satu blok ke blok lainnya di pasar itu. Melihat pedagang berinteraksi dengan pembeli, petugas parkir, hingga ke penjual kantong kresek, atau yang biasa disebut “sangkek asoy”.
Memahami manusia, adalah satu tugas terberat bagi setiap jurnalis. Tentunya, tidak dalam kondisi sedang liputan berbarengan dengan kunjungan seorang pejabat atau tokoh politik.
Dan, pasar adalah tempat yang “paten” untuk itu. Untuk menempa perasaan kita. Perasaan kemanusian dan kepedulian.
Sebab, setebal apapun lembaran koran tempat anda berkerja, subject dari persoalan yang diungkap di sana adalah manusia. Manusia dengan berbagai aspek kehidupan; dari ekonomi hingga politik, budaya hingga lingkungan.
Ekonomi, atau jual beli yang terjadi di pasar, adalah juga budaya. Budaya yang telah berubah, dari barter menjadi penggunaan uang kertas dan logam.
Politik, yakni sisi tergelap dari tawar menawar, sebagai makna asli dari jual beli, yang meniadakan “harga pas” selayak toserba, atau mall.
Lingkungan, yang terasuki budaya tidak peduli. Sebab, meskipun becek bergelimang lumpur, toh orang tetap saja ke pasar itu.
Keterpaksaan? Premanisme? Timbang-menimbang rasa? Semua ada di pasar.
Tetapi, banyak kita yang tidak menyadari itu semua. Pasar Angso Duo, yang kini telah berganti nama menjadi, ehm, jika di-English-kan menjadi “New Two-Swans Market” atau Pasar Angso Duo Baru, terkait erat dengan sejarah reklamasi pertama di Kota Jambi.
Yup, kami, para orang jaman bengen menyebut kawasan ini Tanah Timbun. Sebuah areal berpayau yang ditimbun dengan material tanah yang diangkut entah dari mana, di kitaran tahun ’70-an. Jadilah sebuah pasar, kini.
Erat juga kaitannya dengan banjir 1955 di Kota Makkah. Sebab, pada saat yang sama di tahun 1992, Kota Makkah mengalami banjir, dan pasar bedeng yang sekarang terlupakan itu juga mengalami banjir yang sama tahunnya, setelah banjir tetakhir kali di tahun 1955.
Ups, “biasolah”? Sebagai dalih untuk menolak cara berpikir “sebab – akibat”? Dan menghilangkan tanya “mengapa? untuk mengetahuinya?
Di tahun 1992 itu, Pasar Bedeng itu dibanjiri luapan air, dengan genangan sejak di depan Bioskop Mega (21) hingga ke persimpangan, ups, maaf, Pertigaan Bata.
Di sekitar Simpang, eh, Pertigaan Bata itu, terdapat sebuah sungai kecil, yang berasal dari aliran Sungai Maram atau Sungai Asam, dan perputarannya menjadikan kawasan pasar ini menjadi rawan banjir.
Di sekitar kawasan pasar itu, bertumbuh kembang keturunan dari suku bangsa Arab, India dan Tionghoa, diantara pemukiman Melayu. Sehingga, siapapun saat ini yang menyebut diri “Putera Daerah”, harus memahami pola anti-rasial ini.
Selayak banyak kota di Pulau Sumatera, bahasa pasar adalah Bahasa Minang. Sehingga, jika seseorang yang berusaha belajar bahasa Minang di pasar, tetapi tidak memahami kasanah Bahasa Minang, akan ketara gagoknya.
Atau, menggunakan Bahasa Minang hanya sebagai sebuah strategi untuk menawar barang yang dijual? Sebab dalam tradisi ekonomi pasar yang sesungguhnya, tawaran terendah adalah sepertiga dari harga yang ditawarkan, selanjutnya akan menuju ke titik harga yang sama-sama disetujui oleh penjual dan pembeli.
Terlebih di sebulan Puasa Ramadhan, pasar bedeng itu akan sangat sibuk. Mulai dari penjual penganan berbuka puasa yang dikenal dengan istilah “Pasar Bedug”, para pedagang peralatan ibadah, hingga mendadak seniman yang berjualan “Kartu Lebaran”.
Kini, satu per satu, menghilang, seiring program “Wisata Belanja” yang dikembangkan di kota ini sejak awal 2000-an lalu. Ada banyak mall di kota ini, tempat anda bisa ber-window shopping hingga lelah.
Sebab, ciri utama sebuah mall adalah meniadakan waktu yang berputar. Toh, anda tidak pernah melihat jam dinding digantungkan di dinding mall, agar anda mengingat waktu untuk pulang. Meskipun, tentu saja ada penjual jam di sana.
Lelah? Ya pasti lah haus dan lapar, karena harus berkeliling dari lantai dasar ke lantai teratas. Selanjutnya? Anda akan mampir ke gerai makanan modern, atau yang sering disebut “junk food” itu.
Dan, melupakan makanan lezat bergizi tinggi penuh tradisi selayak Gado-Gado-nya Bu De di Lorong, ups, maaf, Gang Flamboyan di kawasan Broni.
Setelah itu, anda tentu pulang ke rumah. Tetapi, tertanam di bagian alam tak sadar anda, bahwa barang-barang yang anda lihat tadi harus anda beli, suatu saat, jika ada uang. Itulah makna “window shopping” sebenarnya.
Dan, kita semua menyetujui itu. Mengikuti jejak jaman yang terus berubah. Menghilangkan satu persatu pasar bedeng, pasar rombeng, gang siku, dan los. Terakhir, bisa saja pasar beje.
Evolusi? Ups, tentu anda akan menolak menggunakan teori Darwin. Tetapi, itulah yang terjadi. *
* Jurnalis TheJakartaPost