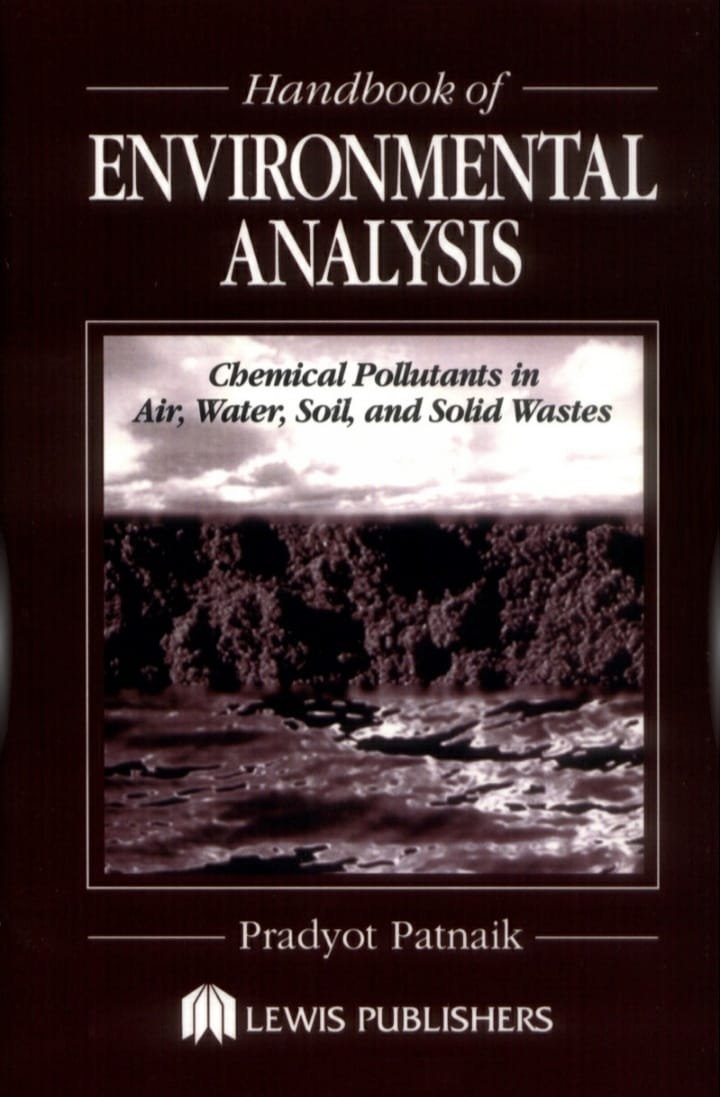*Jon Afrizal
Environment adalah issue sexy, tentunya bagi banyak orang di luar Provinsi Jambi. Kendati, begitu banyak gerakan lingkungan yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai “site project”.
Kembali kita kepada Ton Dietz, yang mengelompokkan gerakan ekologi itu menjadi tiga golongan, pada ulasan sebelumnya, yang merujuk bukunya yang berjudul “Entitlements to natural resources: Countours of Political Environmental Geography” (1996), tiga kelompok itu adalah Eco Fascism, Eco Developmentalism, dan Eco Populism.
Mari kita lihat apa yang secara realita terjadi, di sini, dan tidak melulu berkutat pada teori ala orang kampusan saja. Karena, toh, jurnalis, sesungguhnya, adalah saksi dari setiap situasi dan kondisi yang terjadi.
Eco Fascism yang melihat kondisi lingkungan yang telah rusak, terutama hutan, yang merupakan sebab dari illegal logging, tentunya. Hutan (kami di sini), yang dipenuhi dengan kayu-kayu kualitas ekspor, telah dihanyutkan dalam bentuk kayu balok, melalui sungai-sungai kecil, menuju ke muara. Selanjutnya, di bawa ke luar negeri.
Masih berbekas dalam kenangan, di mana ratusan kayu balok berjajar terikat, memenuhi sungai tepat di belakang Tanah Timbun, atau Pasar Angso Duo Baru saat ini. Dan, itu terjadi selama 20-an tahun lamanya.
Sejauh ini, tidak ada yang bersuara, bahwa “Saya dan Kami bertanggungjawab terhadap banjir yang terjadi saat ini, sebagai akibat dari pohon-pohon berdiameter di atas 40 centimeter yang telah roboh itu!”
Maka, para penganut Eco Fascism yang telah jengah terhadap kondisi ini, mengambil alih komando. Tujuannya, untuk memperbaiki hutan yang rusak itu.
Selanjutnya, maka, hutan pun mengalami berbagai perbaikan. Penanaman kembali, dan berbagai cara agar, hutan yang sebelumnya rusak, dapat baik kembali. Atau, jika mungkin luasannya lebih meluas.
Hutan yang telah ditebang entah oleh “siapa” itu, selanjutnya, malah berubah menjadi kebun sawit. Dan, ehm, diakui atau tidak, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sejak pertama kali, yakni tahun 1991, di sini, juga adalah bagian dari itu.
Asap tebal dan pekat. Dada sesak dan mata perih. Dan, areal perkebunan mono kultur yang semakin hari semakin meluas.
Lalu, Eco Populism mrngambil bagian, di sini. Dengan artian, bahwa hutan dapat saja dimanfaatkan untuk banyak orang. Juga kawasan yang rusak dan terbengkalai.
Ini, jelas, ada kaitan dengan reforma agraria. Dimana, tidak hanya kapital saja yang boleh ber-kebun monokultur, tetapi, mereka yang petani skala kecil pun bisa juga memiliki lahan.
Namun, keinginan untuk memiliki lahan itu, malah berubah menjadi keinginan untuk ber-mono kultur juga. Semua adalah proses sebab-akibat. Harga tandan buah segar (TBS) sawit cukup menggiurkan bagi banyak orang.
Namun, reforma agraria tak kunjung hadir di sini, meskipun semangatnya selalu membara. Dan, perundang-undangan tetap mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan, ehm, jejak kolonialisme itu.
Sebelumnya, semua pihak terkait lingkungan menyatakan bahwa sawit punya efek yang buruk. Baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
Itu dulu, di tahun-tahun awal sawit hadir di sini. Sekarang? Anda sendiri akan mendengar tentang #sawitbaik. Dan, ehm, semua orang sepertinya bicara begitu.
Long Live Deveploment! Atau, jika menggunakan istilah para penganutnya, “pembangunan berkelanjutan”, dimana pembangunan, dalam bentuk apapun, harus tetap dilakukan, untuk kesejahteraan bersama. Yup, Eco Developmentalism.
Dimana, alam (lingkungan) dapat saja dimanfaatkan untuk pembangunan yang terus menerus itu.
Namun, dari sekian teori itu, adakah yang mem-bumi, di sini, di Provinsi Jambi, sebagai “site project”? Nanti dulu, jika ada yang sedang berpikir untuk membenturkan antar mereka. Sebab semuanya dapat bermanfaat, baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun negara, sebagai “alat” yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Hanya saja, disadari atau tidak, semua aliran itu “berjalan sendiri-sendiri”. Eco Fascism terkesan melihat site project ini adalah “bagian dari bumi dengan Pohon Tembesu Terakhir”.
Eco Populism malah membuat banyak orang untuk berpikir memiliki sawit yang harga TBS-nya sangat bergantung dengan hilirisasi-nya, di luar negera ini.
Eco Developmentalism tetap juga mencari celah untuk membangum, sementara itu konflik lahan terus terjadi, dan Pohon Tembesu yang sejatinya masih terdapat beberapa pohon tetap saja terus bertumbangan.
Lahan, tetap bukan milik rakyat, dan telah berganti menjadi lubang menganga. Area bekas tambang batu bara, dan konflik tenurial tetap saja terjadi.
Semua harus bergerak maju; pembangunan tetap harus ada, hutan harus hadir, dan masyakat harus bertumbuh maju perekonomiannya.
“Jalur Tengah”, demikian ku istilahkan. Dimana kemanfaatan lingkungan dapat tetap diambil, dengan risk management yang baik. Juga, benefit sharing bagi masyarakat.
Dan, itu semuanya, harus diikuti banyak pihak. Serta, negara dan elemennya di daerah, harus menjalankan itu.
Sehingga, dengan adanya “Jalur Tengah” ini, slogan yang biasa terdengar, seperti “Negara Tidak Hadir”, misalnya, akan melihat bahwa negara hadir di setiap persoalan lingkungan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dan, itu sudah semestinya ada saat ini. (*)