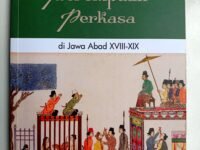Jon Afrizal*
Jika kita bicara data di atas kertas, semua pihak akan mengeluarkan data, yang intinya, “kondisi aman dan terkendali”. Tapi, tentu akan jauh berbeda jika kita semua melihat fakta sebagai sebuah realita.
Pada masa awal pandemi global ini terjadi, yakni sebulan menjelang puasa Ramadhan, saat ini para petani sawah baru saja panen. Bisa saja, seperti data di atas kertas, kita semua berkecukupan untuk stok beras.
Bisa saja, angka lahan pertanian palawija cukup untuk stok sayur-sayuran kita. Itu semua adalah “ok ok saja”.
Faktanya, kita melupakan bahwa padi, yang kemudian menjadi beras, adalah budaya yang sejak lama tumbuh berkembang di sini. Dengan artian, semua orang memakan nasi yang merupakan bentuk transformasi beras di periuk belanga di dapur kita semua.
Tetapi, lagi lagi, apakah stok beras kita berbanding lurus dengan lahan padi sawah? Belum tentu.
Ada sebuah daerah yang disebut sebagai lumbung padi Provinsi Jambi, pada era di bawah tahun 2000-an lalu. Yakni Rantau Rasau, yang dulu adalah bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung. Di sana, banyak di tanam padi ladang, sebutan lain untuk padi gogo rancah, atau padi tadah hujan.
Sekarang, pergilah ke daerah itu. Dan, sila bertanya kepada banyak orang, terkait apa yang ditanam penduduk di sana. Simpulannya, bertanam padi sedikit demi sedikit telah ditinggalkan.
Pun di banyak kawasan yang menjadi lumbung padi Provinsi Jambi. Sebab, adalah tidak salah, jika petani ingin makmur dan menggantikan olahannya menjadi perkebunan monokultur sejenis sawit, misalnya.
Ini semua sangat terkait dengan “ada pembeli maka ada dagangan”. Adalah tidak salah bagi petani untuk memilih itu, sekali lagi, tidak salah.
Namun, berapa banyak stok beras yang berasal dari luar negeri, misalnya, sebut saja Vietnam. Lalu, gula pasir, lalu ketan, dan seterusnya dan seterusnya.
Akumulasi dari itu semua, adalah, Asean Free Trade Area (AFTA), yang telah diinisiasikan sejak awal 2000-an lalu. Atau, secara sederhana dapat disebut dengan “pasar bebas”. Dimana, siapapun atau negara apapun bebas untuk berjualan dimanapun, sesuai dengan area atau pasar yang ditunjuk.
Lalu, apa yang kita jual, atau jika kita gunakan istilah lain, yakni ekspor, ke luar negeri? Apakah berbanding lurus dengan kebutuhan kita?
Kerumitan akan terjadi, jika seluruh bahan-bahan impor itu, tidak masuk ke sini. Jika pun masuk, maka akan berlaku hukum “pembelinya adalah penawar dengan harga tertinggi”.
Tentu saja, akan berhubungan dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Dapatkah anda bayangkan, jika harga sebungkus Nasi Padang yang biasanya anda beli hanya dengan uang kertas pecahan Rp10.000, secara tiba-tiba naik menjadi Rp20.000 atau bahkan lebih?
Tidak mungkin? Wow, tentu saja mungkin. Sebab berasnya adalah beras impor. Dan, dibeli dengan harga yang ditentukan oleh negara penjual atau penanam padi. Lalu, masuk melalui eksportir, kemudian dikenai pajak, dan seterusnya dan seterusnya.
Lalu, terkait yang kita ekspor, sebut saja Tandan Buah Segar (TBS) atau getah karet, atau bahkan biji plastik, akan kembali ke kita dengan bentuk lain, dan kita semua harus membelinya dengan harga yang mahal.
Banyak orang bicara soal industri hulu-hilir sejak tahun 2000-an lalu. Dimana, misalnya, kita tidak lagi mengekspor TBS, melainkan telah dalam bentuk sabun mandi, shampo atau minyak dalam kemasan.
Tetapi, hingga kini itu tidak terwujud. Yang kita hasilkan bagi kebutuhan banyak orang hanyalah “minyak curah” saja. Sedih? Yup, realita memang pahit.
Maka, adalah keharusan bagi siapa saja untuk kembali ke sebutan “negara agraris”. Dimana kita semua awalnya adalah petani dengan berbagai produk pertanian dan hasil hutannya.
Mungkin, pada masa lalu, ada istilah “swasembada beras”. Tetapi, kembali kita semua kepada budaya, bahwa tidak semua kelompok masyarakat adalah pemakan nasi.
Ada masyarakat yang menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Ada juga masyarakat yang menjadikan ubi atau singkong sebagai makanan pokok.
Keseragaman adalah monoton. Itu jika kita menggunakan bahasa para pendukung keberagaman. Dan, itulah yang terjadi saat ini.
Maka, semua orang akan berkata, “itulah susahnyo masyarakat kito ni …” Padahal, siapapun adalah masyarakat. Dan, tentunya, masyarakat diatur oleh pemerintah.
Ada banyak skema yang telah digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi globalisasi sejenis AFTA itu. Kita hanya perlu membuka wacana untuk tidak lagi menanam satu tumbuhan saja, melainkan beragam variasi.
Ini semua, agar tercipta keseimbangan secara real antara produksi dengan kebutuhan lokal kita. Dan tidak melulu hanya data di atas kertas saja.
Yang pada akhirnya, akan berurusan dengan ketahanan pangan. Atau, kemampuan kita untuk menyediakan bahan makanan pokok, tanpa bergantung dengan hasil impor.
Jika pun komoditas pertanian itu berlebih untuk kebutuhan kita semua, maka barulah kita berpikir terkait ekspor.
Ini semua sangat terkait dengan hukum ekonomi yang sangat sederhana sekali. Jika komoditas berlimpah, maka harga akan murah. Dan jika komoditas sedikit, maka harga akan meningkat drastis menjadi mahal.
Sama seperti harga masker di pasaran. Pada awal masa pandemi, harga satu masker buatan rumah tangga adalah Rp10.000. Saat ini, hanyalah Rp10.000 per empat masker.
Jika kita bicara AFTA, tentu saja kita semua harus kembali ke era awal tercetusnya globalisasi itu. Kembaran dari AFTA adalah Asean Free Labor Area (AFLA), atau tenaga kerja yang bebas berkerja di mana saja, sesuai dengan area yang ditentukan.
Apakah kita semua sudah mengantisipasi ini? Sebab tidak akan ada lagi sebutan “Putera Daerah”. Karena semua orang boleh berkerja di mana saja, sesuai dengan kebutuhan akan keahliannya.
Bisa saja, penjual jengkol di Pasar Angso Duo, ups, maaf, “New Two-Swans Market” nanti adalah seorang yang berasal dari Thailand. Atau, seorang yang berasal dari Malaysia akan membuka warung Nasi Padang di simpang tigo, ups, maaf, Pertigaan Sipin. Yup, itulah globalisasi. ***
* Jurnalis TheJakartaPost