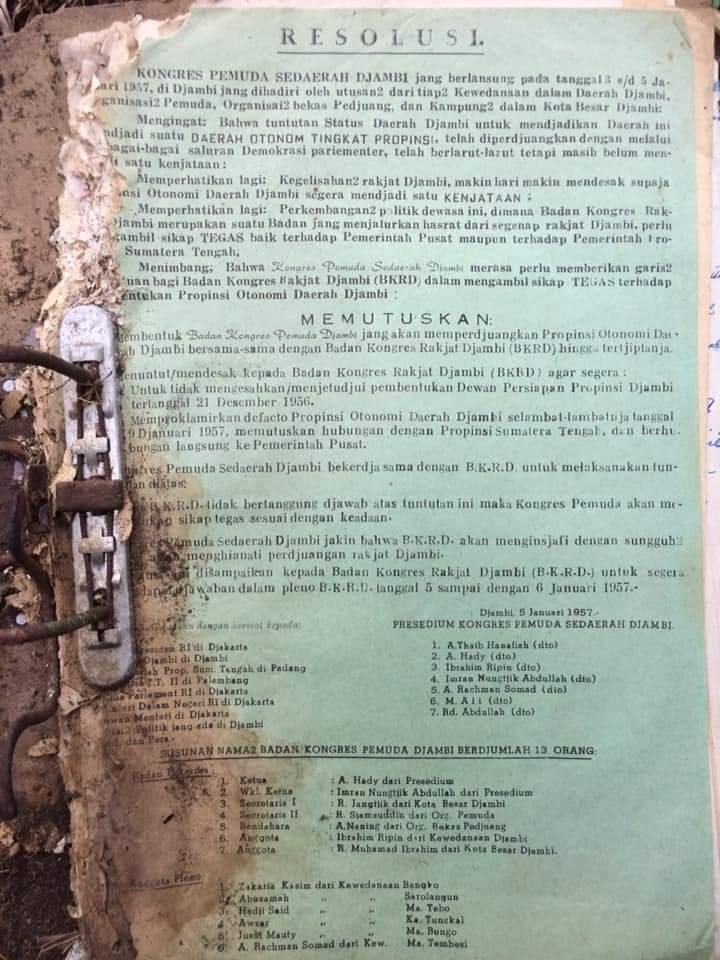Jon Afrizal*
Ruas jalan yang kecil, di pertigaan malam kedua — jika mengikuti waktu salat bagi penganut Islam. Bunyi rentak tapal kuda meningkahi hening lalu lintas.
Sementara Pak Kusir sibuk menyentakkan tali kemudi. Memaksa seekor kuda itu untuk tetap berjalan.
Pada sado itu, di kabin bagian belakang, lutut dua orang penumpang saling bertemu. Sempit.
Sado, yup, dan bukan delman atau bendi. Demikian penduduk Kota Jambi menyebutnya.
Para sais itu mengambil tempat di simpang empat, ups, perempatan maksudnya. Di sebuah sudut kecil antara Jalan Dokter Sutomo, Jalan Dokter Wahidin, Jalan Orang Kayo Hitam, dan Jalan Raden Mattaher.
Sehingga, penduduk kota pun menyebut “terminal” para sais itu dengan sebutan “Simpang Sado”. Yang sangat berkesesuaian dengan sebutan “sado” tadi.
Pada tahun ’90-an dibangun Tugu Pelajar di kawasan ini. Yang hanya beberapa langkah saja ke “Pasar Buah”.
Sado, pada awalnya, di kisaran tahun ’60-an, digunakan oleh banyak penduduk. Tapi, seiring hadirnya kendaraan bermotor, sado mulai kehilangan pamor.
Di tahun ’90-an hingga awal 2000-an, sado lebih banyak digunakan oleh para ibu rumah tangga dari suku bangsa Tionghoa. Mereka banyak berdiam di kawasan Koni, Kebun Kelapo hingga ke Simpang Kasang.
Penduduk Kota Jambi sejak dulu biasa menyebut nama “daerah” atau “kawasan”, dan tidak terlalu peduli dengan “nama jalan”. Terlebih, nama jalan pun kerap berubah-ubah, seiring kebijakan yang juga berubah-ubah. Ups.
Para ibu rumah tangga itu memilih menggunakan sado, adalah karena, sado bisa mengantar mereka memasuki gang hingga ke depan pintu rumah. Selain juga, kabin bagian belakang bisa digunakan untuk meletakkan barang belanjaan.
Wajar saja, ini cerita di masa lalu. Dimana penemu aplikasi ojek online (ojol) belum hadir, tidak hanya di Kota Jambi saja, tapi juga di ibukota negara, Jakarta.
Sejak empat tahun lalu, tidak lagi ditemui sado di Kota ini. Pun google map, sebagai modernisasi petunjuk wilayah saat ini, tidak mengenal kawasan ini.
Sama seperti oplet, yang satu persatu menghilang. Meskipun, para sopir oplet yang “senior” masih mengingat “Simpang Sado” sebagai tempat berhenti warga jika ingin ke Pasar Kota Jambi.
Tidak praktis? Mungkin. Mahal? Boleh jadi? Pariwisata? Ups, maaf, banyak yang melupa.
Para kusir telah on location sejak pukul 09.00 WIB. Mereka akan pulang ke rumah tepat setelah tengah malam.
Para kusir akan menyisir rambut kuda mereka, memeriksa tapal dan kacamata kuda itu setiap pagi hari, sebelum kuda bertugas. Juga memberikan sejenis penampung buat kotoran kuda, tepat di depan si kusir tadi duduk.
Jika tidak, ehm, tentu saja kotoran kuda akan tercecer di mana-mana. Dan merusak pandangan, serta menebarkan bau tak sedap.
Usia kuda, tentunya cukup muda. Agar kuda kuat berdiri tanpa henti di sepanjang hari.
Kecuali jika telah selesai bertugas, kuda boleh membuat gerakan kaki seperti hendak duduk, atau bahkan duduk. Mungkin, jika kuda bisa berbahasa Jambi, ia akan berujar, “Sengal”.
Jika kuda sudah menua dan tidak termasuk bagian dari “tenaga kerja produktif” maka ia akan disembelih. Dagingnya akan dijual di pasar-pasar yang dekat dengan tempat si pemilik kuda bertempat tinggal.
Harga daging kuda, biasanya, setara dengan harga daging sapi. Tapi, serat dari daging kuda tidak seperti daging sapi.
Sangat alot, dan butuh waktu lama untuk merebusnya. Hingga benar-benar renyah untuk dikunyah geligi, ketika dihidangkan sebagai gulai bersantan kelapa.
Unik? Adakah dari pembaca yang masih mengingat ini?
Jika ada yang berpikir sado sebagai sarana pariwisata komersil, mungkin para sais dan kudanya tetap hadir hingga hari ini.
Sila perbandingkan sendiri. Pada tahun ’90-an, tarif untuk satu kali jalan adalah Rp 15.000. Pada tahun 2000-an adalah Rp 25.000.
Wow, tentu pemasukan yang lumayan bagi para kusir, dan, ehm petugas pajak dan retribusi, tentunya. But who’s care about that, anyway…
Di beberapa kota, terutama di Pulau Jawa, delman, begitu sebutan mereka, masih tetap hadir menghiasi jalan raya. Sebagai daya tarik wisata.
Ada sebuah lagu, tentang ini;
“Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota
Naik delman istimewa ku duduk di muka”
“Naik Delman” adalah lagu ciptaan Pak Kasur, atau yang bernama lengkap Soerjono. Ia adalah pencipta lebih dari 200-an lagu anak-anak, dan meninggal dunia pada tahun 1992 lalu, di usia 78 tahun.
Jika ada yang berperspektif bahwa sado adalah “tidak berperikebinatangan”, maka dapat dibandingkan dengan jigsaw di India, atau bahkan gerobak dorong di Pasar Angso Duo, ups, maaf, New Two-Swans Market, sana.
Philipina saja masih melestarikan jeepney, sebagai sebuah maskot, dan juga cara menarik wisatawan. Padahal, jeepney adalah transportasi massal, yang berasal dari kata “jeep” untuk kendaraan perang dunia kedua lalu.
Sesuai, memang. Sebab kata “jeep” dalam kasanah bahasa Inggris sendiri berasal dari “GP” atau “general purpose”.
Sejauh ini mereka berpikir tentang bagaimana mengembangkan pariwisata. Tentang sesuatu yang dapat dijual untuk kategori “jasa”.
Padahal, Kota Jambi dulu juga mengenal kendaraan jeep Willy’s, untuk transportasi massal dari Terminal Rawasari – Kota Baru, yang sekarang ini menjadi pusat Pemerintahan Kota Jambi.
Bagaimana dengan kita? Belum ada kata terlambat, jika anda mau melongok mencarinya di banyak “kampung” di kota ini. Meskipun, ya, sado yang tanpa kuda lagi.
Namun, kuda tetap bisa dicari di Provinsi Sumatera Barat. Mereka mengenal “Pacuan Kuda”, dan hanya butuh niat untuk mencari bibit kuda yang baik untuk kembali menghidupkan “Simpang Sado”. (*)